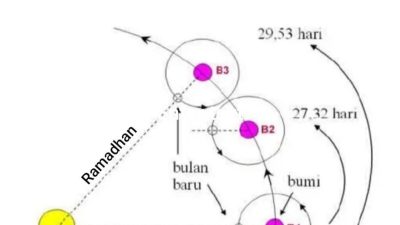MajmusSunda News, Garut, 5 Januari 2026 – Pada mulanya, alam berbicara kepada manusia dengan cara yang tenang dan bersahabat. Ia menyampaikan pesannya melalui aliran sungai yang jernih, melalui hutan yang teduh dan sejuk, melalui tanah yang subur, serta melalui pergantian musim yang berjalan teratur. Alam tidak memaksa manusia untuk mendengar. Ia cukup hadir, setia menjaga keseimbangan hidup. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, bahasa alam berubah. Ia tidak lagi berbisik, melainkan berteriak. Banjir datang berulang tanpa jeda. Tanah longsor merenggut rumah dan harapan. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini menjelma saluran limbah. Hutan yang dahulu menjadi pelindung bumi tinggal nama dalam ingatan.
Fenomena ini sering kita sebut sebagai bencana alam. Kata “alam” seakan menjadi tameng yang membebaskan manusia dari tanggungjawab. Seolah-olah semua ini murni takdir, musibah yang datang dari luar kuasa manusia. Padahal, semakin banyak kajian menunjukkan bencana bukanlah peristiwa alamiah semata. Ia adalah hasil dari relasi yang timpang: antara manusia dan alam, manusia dan manusia, serta manusia dan nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjaga kehidupannya (Capra, 1996; Keraf, 2010). Bencana, dengan demikian, bukan hanya peristiwa fisik. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan wajah peradaban manusia.
Dalam perspektif ekologi kritis, bencana tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan sistem yang lebih besar. Sistem ekonomi kapitalistik yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas. Kebijakan pembangunan yang mengorbankan alam demi keuntungan jangka pendek. Budaya konsumsi yang memutus kesadaran manusia dari batas-batas ekologis bumi (Harvey, 2005). Karena itu, banjir tidak dapat dipisahkan dari tata ruang yang serampangan. Krisis pendidikan tidak terlepas dari logika pasar tenaga kerja. Konflik sosial berkaitan dengan ketimpangan ekonomi. Kemiskinan struktural lahir dari penguasaan sumber daya oleh segelintir orang. Rapuhnya institusi keluarga berakar pada tekanan hidup yang kian tidak manusiawi. Semua ini bukan krisis yang terpisah. Ia adalah simpul-simpul dari satu krisis besar: krisis peradaban modern.
Fritjof Capra (1996) menyebutnya sebagai krisis sistemik—krisis yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan spiritual sekaligus. Ketika satu bagian rusak, bagian lain ikut terguncang. Alam rusak, masyarakat rapuh. Nilai runtuh, manusia kehilangan arah. Menariknya, apa yang kini dibahas dalam teori-teori modern sebenarnya telah lama hidup dalam kearifan lokal Nusantara. Dalam khazanah Sunda klasik, alam tidak pernah dipahami sebagai benda mati. Alam adalah mitra hidup, bagian dari keluarga besar kehidupan. Ketika manusia menjaga alam, alam pun menjaga manusia. Namun ketika manusia melampaui batas, keseimbangan pun terganggu. Dalam ungkapan Sunda dikenal kalimat: “balikna alam kana kalakuan manusa”—alam akan kembali kepada manusia sesuai dengan perbuatannya (Danasasmita, 1987). Ungkapan ini bukan ancaman, melainkan pengingat etis. Alam tidak membalas dendam. Ia hanya bekerja sesuai hukum keseimbangan. Ketika hutan ditebang, air kehilangan penyangga. Ketika sungai dicemari, kehidupan terganggu. Ketika tanah dirusak, manusia menuai akibatnya. Di titik inilah krisis ekologis bertemu dengan krisis moral. Kerusakan alam bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan etis.
Refleksi ini berdiri pada ruang dialog antara kajian ekologis modern dan spiritualitas kenabian, khususnya konsep “Asmâ’ Harîsh”—maqâm penjagaan dan perlindungan. Dari dialog ini, tulisan ini bertujuan untuk:
1. Memahami bencana sebagai gejala multidimensional.
2. Menelusuri kerusakan alam sebagai akibat paradigma eksploitatif.
3. Menawarkan rekonstruksi nilai penjagaan kehidupan melalui integrasi kearifan Sunda dan etika kenabian.
Kajian bencana modern menolak pandangan bahwa manusia hanyalah korban pasif. Wisner et al. (2004) menegaskan bencana adalah hasil dari kerentanan sosial yang dibangun oleh struktur ekonomi dan politik. Dengan kata lain, manusia adalah aktor utama dalam produksi risiko. Bencana terjadi bukan hanya karena hujan deras atau gempa bumi, tetapi karena manusia gagal menjaga. Capra (1996) menjelaskan akar krisis ekologis terletak pada cara pandang mekanistik dan reduksionistik manusia modern. Alam dipahami sebagai mesin. Kehidupan direduksi menjadi komponen-komponen yang bisa dieksploitasi. Manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa, bukan bagian dari ekosistem. Keraf (2010) menambahkan, krisis ini diperparah oleh hilangnya etika ekologis. Alam tidak lagi dipandang memiliki nilai intrinsik, melainkan nilai ekonomi semata. Dalam konteks kapitalisme global, cara pandang ini dilembagakan melalui kebijakan pembangunan dan logika pasar (Harvey, 2005). Sebaliknya, Iskandar (2001) menunjukkan masyarakat Sunda tradisional memiliki sistem pengetahuan ekologis yang berbasis etika relasional. Prinsip teu nganyenyeri alam—tidak menyakiti alam—menjadi dasar sikap hidup. Pepatah “leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak” bukan sekadar ungkapan, melainkan diagnosa ekologis yang sangat tepat.
Dalam spiritualitas Islam, khususnya dalam pemikiran Ibna ʿArabî, kenabian tidak hanya berfungsi sebagai penyampai wahyu. Nabi hadir sebagai penjaga kesadaran umat. Ia melindungi manusia dari kelalaian spiritual (“ghaflah”) dan kerusakan moral (Ibna ʿArabi, 2002). Konsep “Harîsh” menggambarkan maqâm protektif Nabi Muhammad: sosok yang sangat peduli, waspada, dan menjaga umat dari bahaya lahir dan batin. Seyyed Hossein Nasr (1996) menegaskan, dimensi ini menjadikan kenabian sebagai kekuatan etis yang menjaga keseimbangan kosmos. Kerangka ini sangat relevan dengan krisis kontemporer. Ketika manusia kehilangan sikap “harîsh”—kehati-hatian dan penjagaan—maka kerusakan menjadi keniscayaan (Widyadiningrat, 2025). Dalam kerangka ini, banjir bukan sekadar limpahan air. Ia adalah simbol air yang kehilangan rumahnya. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan tata ruang yang abai menunjukkan absennya sikap penjagaan dalam pembangunan (Keraf, 2010).
Dampak banjir selalu bersifat sosial. Masyarakat miskin menjadi korban utama karena tinggal di wilayah rentan (Wisner et al., 2004). Banjir dengan demikian adalah cermin ketimpangan dan kegagalan etika pembangunan. Bencana tidak hanya terjadi di alam. Ia juga terjadi dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang tercerabut dari nilai dan budaya melahirkan manusia yang terampil secara teknis, tetapi rapuh secara moral (Freire, 1970). Dalam perspektif Sunda, hilangnya orientasi “jalma masagi” menandai kegagalan pendidikan sebagai penjaga nilai. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang seimbang antara rasa, pikir, dan laku (Rosidi, 2009).
Krisis yang sama berlanjut dalam kehidupan sosial. Modal sosial melemah (Putnam, 2000). Solidaritas terkikis oleh individualisme dan kompetisi. Ekonomi lokal terpinggirkan oleh sistem global (Schumacher, 1973). Di tingkat keluarga, tekanan ekonomi dan budaya kerja membuat keluarga kehilangan fungsi protektifnya. Angka perceraian meningkat, dialog melemah, dan anak-anak tumbuh dalam kekosongan nilai (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Sampah, sungai tercemar, dan eksploitasi hutan adalah tanda matinya etos penjagaan ekologis. Padahal, dalam kearifan Sunda dan spiritualitas Islam, penjagaan adalah inti etika hidup.
Ibna ʿArabî menggambarkan Nabi sebagai penjaga yang membangunkan kesadaran dan mengembalikan manusia pada jalan kebenaran (Ibna ʿArabî, 2002). Maqâm “Harîsh” mengandung tiga konsep utama: “hifdh” (penjagaan), ”himâyah” (perlindungan), dan “wiqâyah” (pencegahan bahaya) (Widyadiningrat, 2025). Dalam konteks ekologis, maqâm ini menuntut manusia menjadi penjaga alam, bukan penakluknya. “Manusia bukan pemilik bumi, melainkan penjaga titipan kehidupan.”
Rekonstruksi nilai kehidupan menuntut pergeseran paradigma dari eksploitasi menuju penjagaan. Alam perlu diposisikan kembali sebagai guru etika (Keraf, 2010). Pembangunan harus dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia (Schumacher, 1973). Pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia utuh (Rosidi, 2009). Agama dihadirkan sebagai etika ekologis dan sosial yang hidup (Nasr, 1996). Refleksi ini menegaskan, bencana ekologis dan sosial adalah cermin retaknya etos penjagaan dalam peradaban modern. Krisis ini bersumber dari paradigma eksploitatif yang memutus relasi manusia dengan alam, sesama, dan nilai spiritual.
Integrasi kearifan Sunda klasik dan maqâm “Harîsh” menawarkan jalan pulang—jalan untuk kembali menjadi manusia yang menjaga, melindungi, dan merawat kehidupan. Ketika manusia belajar kembali menjaga, mungkin alam akan berhenti berteriak, dan kembali berbisik dengan bahasa kasih.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences. London: Sage Publications.
2. Capra, F. (1996). The web of life: A new scientific understanding of living systems. New York, NY: Anchor Books.
3. Danasasmita, S. (1987). Kehidupan masyarakat Sunda dalam naskah-naskah lama. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York, NY: Continuum.
5. Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
6. Ibna ʿArabî. (2002). Al-Futûhât al-Makkiyyah (Vols. 1–4). Beirut: Dâr Shâdir.
7. Iskandar, J. (2001). Manusia, budaya, dan lingkungan: Kajian ekologi manusia. Bandung: Humaniora Utama Press.
8. Keraf, A. S. (2010). Etika lingkungan hidup. Jakarta: Kompas.
9. Nasr, S. H. (1996). Religion and the order of nature. New York, NY: Oxford University Press.
10. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, NY: Simon & Schuster.
11. Rosidi, A. (2009). Manusia Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.
12. Schumacher, E. F. (1973). Small is beautiful: Economics as if people mattered. London: Blond & Briggs.
13. Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters (2nd ed.). London: Routledge.
14. Widyadiningrat, Noer. (2025). 201 Visi Nami Muhammad SAW.: Perjalana Cinta Ibna ´Arabî. Jakarta, Meta Aksara.
*****
Judul: ETIKA INVESTASI ALAM — Refleksi Bencana Global
Penulis: NOER Widyadiningrat (Pembelajar Djatirumasa)