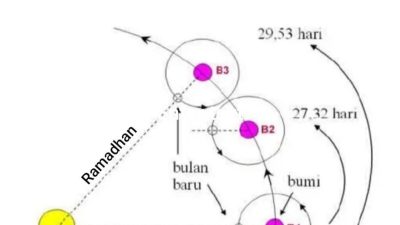MajmusSunda News, Garut, 10 Januari 2026 – Fikih sering kali dipahami secara sempit sebagai daftar aturan halal dan haram yang mengatur perilaku lahiriah manusia. Pemahaman ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jelas belum utuh. Jika fikih hanya diperlakukan sebagai kumpulan regulasi normatif, maka kita kehilangan dimensi terdalamnya sebagai ilmu yang hidup—ilmu yang tumbuh bersama sejarah, pergulatan sosial, dan pencarian spiritual umat Islam selama lebih dari satu milenium (Hallaq, 1997).
Dalam sejarah Islam, fikih tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai jawaban atas tantangan nyata: bagaimana menjaga kemurnian wahyu di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus bergerak. Dari sinilah fikih berkembang bukan sekadar sebagai sistem hukum, tetapi sebagai panduan reflektif yang menghubungkan manusia dengan Tuhan sekaligus dengan sesamanya. Namun, perjalanan panjang fikih juga melahirkan ketegangan laten. Di satu sisi, terdapat pendekatan yang menekankan struktur hukum, metodologi, dan kepastian normatif. Di sisi lain, tumbuh pendekatan yang menaruh perhatian pada makna batin, hikmah ilahi, dan dimensi spiritual syariat. Dua kecenderungan ini sering diposisikan sebagai kutub yang saling berhadapan.
Dua tokoh besar yang merepresentasikan kecenderungan tersebut adalah Imam al-Syafi‘i (w. 204 H) dan Muhyiddîn Ibna ‘Arabî (w. 638 H). Imam al-Syâfi‘i dikenal sebagai arsitek metodologi fikih yang sistematis. Melalui perumusan usul fikih, ia berupaya menjaga otoritas Al-Qur’an dan Sunnah agar tidak larut dalam subjektivitas manusia atau praktik lokal yang tidak terverifikasi (Al-Syâfi‘i, 2004). Sementara itu, Ibna ‘Arabî hadir sebagai sufi-filosof yang membaca syariat sebagai manifestasi kehendak Ilahi yang sarat makna metafisik dan spiritual (Chittick, 1989).
Kajian-kajian sebelumnya sering kali memosisikan keduanya dalam relasi oposisi: fikih versus tasawuf, hukum versus makna, lahir versus batin. Cara pandang dikotomis ini melahirkan kesan, pemikiran al-Syâfi‘i dan Ibna ‘Arabî saling menegasikan. Tulisan ini justru bergerak dari asumsi sebaliknya: perbedaan mereka adalah perbedaan tingkat dan fungsi pemahaman fikih, bukan pertentangan esensial. Untuk menjembatani dua horizon ini, tulisan ini menggunakan konsep “Asmâ’ Muhammad al-Jâmiʿ”, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibna ‘Arabî. “Al-Jâmiʿ” dipahami sebagai prinsip penyatuan yang aktif—menghimpun lahir dan batin, hukum dan makna, individu dan kosmos (Widyadiningrat, 2025). Dari sinilah gagasan “fikih kosmopolitan” menemukan pijakannya.
Fikih dapat dibayangkan sebagai sebuah pohon kehidupan. Akarnya adalah wahyu, batangnya adalah metodologi, dan cabang serta daunnya adalah praktik sosial manusia. Jika perhatian hanya tertuju pada batang dan daun, pohon tampak kaku dan mekanis. Namun ketika akarnya disadari, pohon itu hidup—memberi keteduhan, menumbuhkan buah hikmah, dan menopang ekosistem di sekitarnya. Dalam pandangan Imam al-Syâfi‘i, fikih berfungsi sebagai fondasi keteraturan umat. Ia lahir pada masa ketika praktik hukum Islam sangat beragam dan berpotensi terfragmentasi. Dengan menyusun usul fikih, al-Syâfi‘i membangun kerangka epistemologis yang memungkinkan hukum Islam diajarkan, diuji, dan diterapkan secara konsisten lintas ruang dan waktu (Al-Syâfi‘i, 2004). Fikih, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai “hâfidh”—penjaga. Ia menjaga agama dari infiltrasi hawa nafsu, kepentingan politik, dan inovasi yang tidak berlandaskan dalil. Tanpa struktur ini, hukum berisiko larut dalam relativisme dan kehilangan legitimasi publik (Hallaq, 1997). Ibna ‘Arabî tidak menolak fungsi penjagaan ini. Ia tidak menafikan fikih sebagai sistem hukum. Yang ia kritik adalah reduksi fikih menjadi sekadar prosedur legal. Baginya, hukum tanpa makna adalah tubuh tanpa ruh. Ibna ‘Arabî menerima “kasyf”, yakni pengalaman penyingkapan batin, sebagai sarana memperdalam pemahaman individu tentang hikmah Ilahi. Namun ia menegaskan batas yang jelas: “kasyf” tidak boleh menjadi dasar hukum publik. Ia berfungsi pada ranah pemaknaan, bukan legislasi (Ibna ‘Arabî, 1999). Dalam perspektif ini, fikih menjadi jalan transformasi batin. Pertanyaan fikih tidak berhenti pada “apa hukumnya?”, tetapi berlanjut pada “apa makna eksistensial hukum ini bagi relasi manusia dengan Tuhan?”
Salah satu ciri paling menonjol dalam tradisi fikih adalah “ikhtilâf”, perbedaan pendapat. Bagi Imam al-Syâfi‘i, ikhtilaf merupakan konsekuensi tak terelakkan dari keterbatasan manusia dalam memahami dalil. Kebenaran hakiki tetap satu di sisi Tuhan, tetapi hasil ijtihad manusia dapat beragam. Dari sini lahir etika intelektual yang khas: rendah hati, terbuka pada koreksi, dan menghargai pandangan lain (Hallaq, 1997). Ibna ‘Arabî memandang “ikhtilâf” dari horizon yang lebih luas. Baginya, perbedaan bukan hanya akibat keterbatasan manusia, melainkan keniscayaan ontologis. Setiap pendapat mencerminkan “tajallî Ilahi”, manifestasi kehendak Tuhan yang berbeda sesuai kesiapan spiritual penerimanya. Dalam pandangan ini, keragaman bukan ancaman bagi kebenaran, melainkan bagian dari harmoni kosmik itu sendiri (Chittick, 1989). Di sinilah prinsip “al-Jâmiʿ” bekerja: menyatukan perbedaan tanpa menghapus keberagaman, menjadikan “ikhtilâf” sebagai ruang perjumpaan, bukan medan pertentangan.
Secara bahasa, “al-Jâmiʿ” berarti “yang menghimpun” atau “yang menyatukan”. Dalam Al-Qur’an, Allah digambarkan sebagai Zat yang menghimpun seluruh manusia pada Hari Kiamat (Q.S. Ali ‘Imran: 9). Bagi Ibna ‘Arabî, “al-Jâmiʿ” bukan sekadar sifat ilahi, tetapi sebuah maqâm metafisik yang menyatukan bumi dan langit, lahir dan batin, syariat dan ma‘rifat. Ia menafsirkan bahwa melalui sifat ini, Nabi Muhammad menjadi medium manifestasi Asmâ’ Muhammad secara total. Huruf-huruf Jâmiʿ—jîm, alif, mîm, ‘ayn—melambangkan prinsip kosmik: daya tarik penyatuan, kesatuan eksistensial, penjagaan komunitas, dan penglihatan batin yang menembus makna terdalam realitas (Ibna ‘Arabî, 1999). Dalam horizon ini, fikih tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan kaku, melainkan sebagai seni menyatukan hukum dan kasih, ketertiban dan kebijaksanaan. “Al-Jâmiʿ” menjadi jembatan yang menghubungkan fikih al-Syâfi‘i sebagai struktur hukum dengan fikih Ibna ‘Arabî sebagai pemahaman makna batin.
Bagi Imam al-Syîfi‘i, “faqîh” ideal adalah sosok yang kuat hafalan dalilnya, disiplin metodologinya, dan sangat berhati-hati dalam berfatwa. Ia adalah penjaga hukum, penopang otoritas syariat, dan benteng dari penyimpangan (Hallaq, 1997). Ibna ‘Arabî memperluas horizon ini. “Faqîh” ideal tidak cukup hanya menguasai hukum, tetapi juga harus menjadi pembaca makna batin hukum. Ia taat pada syariat sekaligus bersih batin, sehingga mampu menangkap hikmah Ilahi yang tersembunyi di balik ketentuan lahiriah (Chittick, 1989). Dalam praktik sehari-hari, fikih kosmopolitan ini terwujud sebagai sikap yang tegas namun empatik, disiplin namun reflektif: menegakkan hukum tanpa kehilangan dimensi moral dan spiritualnya.
Sejarah Islam menunjukkan bahwa fikih normatif dan pendalaman batin bukan dua kutub yang saling meniadakan. Banyak ulama besar adalah fuqaha sekaligus sufi, membuktikan hukum dan makna dapat berjalan beriringan. Dalam sintesis ideal, fikih al-Syâfi‘i menjaga struktur hukum, sementara fikih Ibna ‘Arabî menghidupkan makna dan etika spiritual hukum (Nasr, 2006). Dengan perspektif “al-Jâmiʿ”, fikih menjadi jalan penyatuan: antara hukum dan makna, individu dan komunitas, manusia dan Tuhan. Inilah yang dapat disebut sebagai fikih kosmopolitan—fikih yang berakar kuat pada wahyu, terbuka pada keragaman, dan peka terhadap dimensi spiritual serta kemanusiaan universal.
Dalam dunia modern yang plural dan saling terhubung, fikih kosmopolitan menawarkan kerangka etis yang penting. Fikih al-Syâfi‘i menjaga struktur hukum dan hak publik, sementara fikih Ibna ‘Arabî menumbuhkan empati, kedalaman spiritual, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam pendidikan, prinsip “al-Jâmiʿ” mendorong kurikulum yang menyeimbangkan hukum, etika, dan spiritualitas. Dalam masyarakat multikultural, ia mengajarkan cara menghargai perbedaan tanpa kehilangan kesatuan. Dalam etika global, ia membuka jalan bagi harmoni antara manusia dan lingkungan, antara norma dan kasih, antara kepentingan individu dan tanggungjawab kolektif.
Perbedaan antara Imam al-Syâfi‘i dan Ibna ‘Arabî bukanlah kontradiksi, melainkan perbedaan maqâm dalam memahami fikih. Al-Syâfi‘i membangun fondasi hukum dan menjaga otoritas wahyu. Ibna ‘Arabî menghidupkan fikih sebagai jalan pemahaman makna Ilahi. Melalui “Asmâ’ al-Jâmiʿ”, fikih tampil sebagai jalan penyatuan—sebuah jalan pulang bagi jiwa manusia. Ia bukan sekadar sistem aturan, melainkan seni hidup yang menuntun manusia menuju keadilan, harmoni, dan makna terdalam eksistensi.
Daftar Pustaka
1. Al-Syafi‘i, M. (2004). Al-Risâlah fî Ushûl al-Fiqh. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
2. Chittick, W. C. (1989). The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany: SUNY Press.
3. Hallaq, W. B. (1997). A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Ibna ‘Arabî, M. (1999). Al-Futûhāt al-Makkiyah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
5. Nasr, S. H. (2006). Islamic Spirituality: Foundations. New York: Crossroad Publishing.
Qur’an. (2008). Ali ‘Imran 3:9. The Quranic Arabic Corpus.
6. Widyadiningrat, N. (2025). 201 Visi Nami Muhammad: Jalan Cinta Ibna ´Arabi. Jakarta: Meta Aksara.
*****
Judul: FIKIH KOSMOPOLITAN: Dialog Penyatuan Imam al-Syâfi‘i dan Ibna ‘Arabî
Penulis: NOER Widyadiningrat (Pembelajar Djatirumasa)